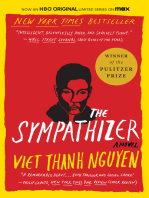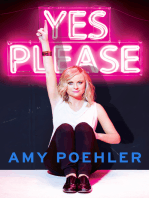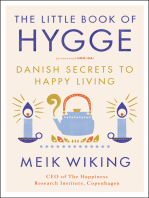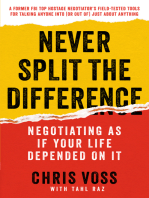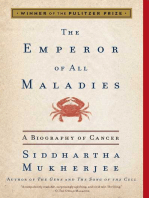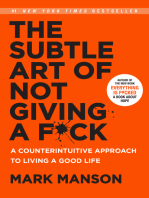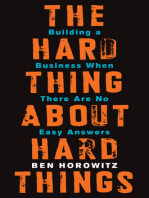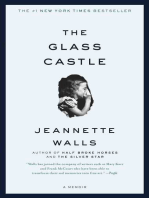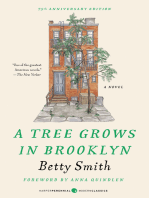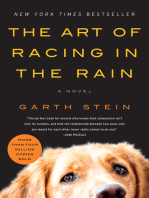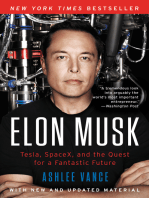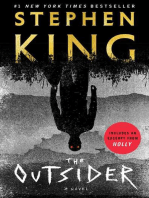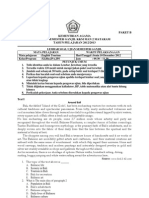Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Buku Universe Within PDF
Încărcat de
adang hermeneutikaTitlu original
Drepturi de autor
Formate disponibile
Partajați acest document
Partajați sau inserați document
Vi se pare util acest document?
Este necorespunzător acest conținut?
Raportați acest documentDrepturi de autor:
Formate disponibile
Buku Universe Within PDF
Încărcat de
adang hermeneutikaDrepturi de autor:
Formate disponibile
Tinjauan Buku
The Universe Within:
A Balinese Village through its Ritual Practices
Author: Arlette Ottino
Editions Karthala Press, Paris.
2000, 320 pages.
Reviewed by: I Gede Pitana
(Udayana University)
This book is a revised version of the author’s thesis at the Department of Anthropology,
Research School of Pacific and Asian Studies, submitted in 1991. With some expansion, the
book is basically an anthropological study of ritual in a small mountainous village in Bali, in the
regency of Tabanan. Based on her fieldwork data gathered in 1986–1987, the author applies
various theoretical frameworks in analyzing the precedence and hierarchy of the complemen-
tary opposites of various aspects of the village and its ritual life.
The book contributes significantly to the body knowledge on Balinese cultural practices as
well as strengthens some previously well-known prepositions. To some extent, the village is
positioned as an independent entity, without any relation to other villages or supra-village struc-
ture. When the supra-village structure is mentioned, it is the Kingdom of Tabanan, which is in
fact now no longer in existence. Reading this book, it seems that the notion of Korn’s (1932)
‘village republic’ is enlivened. The theory that ‘the individual’ does not exist in Bali—because
of the strong collective nature of the society—is also gaining a new support from the author
when she writes that ‘life outside the desa adat becomes unconceivable’ (pp.25), or ‘the conti-
nuity of the society still takes primacy over individual needs’ (pp.277). She also aptly restates the
submission of Balinese society over the unseen world, that the invisible world (niskala) takes
precedence over the visible one (sekala). She also adds that sekala and niskala cannot be put
as a simple opposition, but as two dimensions of the world in Balinese beliefs and practices.
The author also enriches the knowledge of the variations—or better, contradictions—found
among villages in Bali. Some examples can be given below. Although Bali is known as a patri-
lineal society, there is also a practice of nyeburin in marriage, whereby the groom is integrated
to the bride’s lineage. While in Buleleng or Klungkung this practice is hardly found (see, e.g.
Geertz and Geertz 1975; Barth 1993), this is not uncommon in the village understudy. A more
striking contrast shows when nyeburin practice in the village is not only done by couples who
have no son to continue the generation. It is not rare to find the practice occurring to families
who already have had sons. An other variation that might also be of interest is the practice of
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 93
marriage among the first cousins. While this marriage is only practiced by noble families in other
regions, and prohibited for the common people , in Tabanan this practice is preferred by com-
moners (pp.264ff). Small but principal variation is also put forward by the author, in the naming
system of children. In other parts of Bali in general, the birth-order name of a family consisting of
four children starts from, i.e. Wayan (or Putu or Gede) as the first child, Made (or Nengah or
Kadek ), Nyoman (or Komang), and Ketut. After the fourth (Ketut) as the fourth child, the cycle
is back to the first (Wayan), the second, etc. In the village under discussion (and also the
surrounding villages), on the other hand, the birth-order name consists of five: is Wayan, Nengah,
Made, Nyoman, and Ketut. Interestingly, children born after the fifth are all called Ketut, for the
reason that it is impossible to return to the first after reaching the end of the circle (pp.269).
Aside from teh book’s contributions, it seems that the author unconsciously analyses the
practices in the village in a linear, mono-variate in nature, to support her previously held prepo-
sition. When she found the nyeburin practice among families who have sons, she argues that the
practice can be seen as a strategy ‘to maximize the continuity of the family through the use of the
fertility of a woman who is also a member of the purusa line as well as through men’. This
argument understates the importance of other factors, notably economic or land ownership,
which is common in agrarian based community such as Bali. From empirical observation in
Tabanan areas, nyeburin is generally practiced by relatively well to do families, while the hus-
band is generally from the relatively poorer, otherwise from the same lineage (cousins or of the
same sanggah gede). In analyzing the precedence of male-female of the same configuration to
that desa adat-subak , this monovariate-linear model is repeated. It gives an impression that desa
adat and subak match in physical boundaries of membership. Although sometime overlaps, in
fact subak and desa adat are of different entities. There can be several subak within a desa adat,
while on the other hand a subak may cover ricefield from several desa adat. A member of desa
adat can be a member of more than one subak , and this is not unusual (see e.g. Pitana 1994). For
this reason, it is not defendable to make a parallel of male-female to desa adat-subak . Similar
analysis is also applied to husband-wife, in the example that the husband is addressed as ‘beli’
(elder brother), while the wife is addressed as ‘adi’ (younger sister). This interpretation neglects
the fact that the term of address is mainly associated with age, where wives are usually younger
than husbands. If the husband is younger (there are cases of this), it is no way he will address his
wife as ‘adi’ (younger sister).
As of other case studies in anthropology, there is a danger in interpreting that the materials
under discussion represent Bali. Hence, a careful reading is needed to ensure, when the author
talks about Bali or specially the village under discussion. Furthermore, as the data used were
gathered in 1989–1987, while the book was published in 2000, careful reading is again needed,
regarding some data might have been obsolete. In addition, the author seems to be ignorant of
several works published on related materials by Balinese researchers and academicians, both
during her study in Bali and especially after she submitted her thesis. Out of 144 references, only
three Balinese works are included, or less than 2%. It seems to be no academic writing has been
published by Balinese experts of worth quoting. Or, the author might put academicians in hier-
archy or precedence: Western-Balinese.
94 ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003
References
Pitana, I.G. (ed.)
1994 Subak, Sistem Irigasi Tradisional di Bali. Denpasar: Upada Sastra Press.
Geertz, H and C. Geertz
1975 Kinship in Bali. Chicago and London: University of Chicago Press.
Korn, V.E.
1932 The Republic of Tenganan Pagrisingan.
Barth, F.
1993 Balinese Worlds. Chicago: University of Chicago Press.
Sisters and Lovers:
Women and Desire in Bali
Author: Megan Jennaway,
Rowman and Littlefield Publishers, Inc., Lanham.
2002, 308 pp. including Glossary, 6 appendices, Bibliography and Index.
Reviewed by: Lyn Parker
(University of Western Australia)
I really enjoyed this book: it’s engagingly written and easy to read and the issues raised are
long-neglected and important. According to the author, it is an ethnography of ‘desire’, a claim
with which I take issue below, but it is an ethnography of the everyday experience of (mainly)
young women, based on long-term fieldwork in a village just south of Lovina, on the north coast
of Bali.
‘Desire’ (Chapter 2) is an emerging field in anthropology, with scholars attempting to go
beyond the Freudian idea of desire as a libidinal drive. Jennaway is attracted by Onghourian’s
work, The Puppet of Desire: The Psychology of Hysteria, Possession and Hypnosis, which
posits, in contravention of Freud, that the seat of desire is not the Unconscious, nor the self who
is experiencing the desire, but rather that ‘it is desire that brings the self into existence’ (1991:11
in Jennaway 2002:19). In this theory, desire is presumably brought into existence in inter-sub-
jective or social relations; Jennaway stresses its cultural constructedness. My problem with this
is that ‘desire’ remains an enigma—its origin is a sort of ‘Who made god’ question and it is only
explicable in terms of its expression, which must be culturally relative. My assumption that
desire was strongly associated with sexuality caused me to be surprised by Chapter 3, entitled
‘Producing Desire: Village Economy and Social Organisation’—a fairly conventional analysis of
work roles, access to the means of production, etc., with important insights into the ways women
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 95
are excluded from political and economic power, particularly in marriage. In fact, much of the
book has to do with marriage and how women feel as they negotiate the rocky path to and
beyond marriage. Sexual desire is an aspect of this, but this book is not principally about sexual
desire.
However, theory is not important in this book and it contributes new understandings of Ba-
linese society. Jennaway explicitly targets the traditional muteness and objectification of women
in Bali, and aims to make women the articulate subjects of this book. In this, Sisters and Lovers
succeeds admirably. In Balinese society and in the anthropological literature on Bali women’s
voices have traditioanlly been suppressed (Chapter 1). In focusing on female experience and
subjectivity, and especially in attending to young women’s unconventional expressions of desire
(e.g. deception of parents, ‘hysterical’ attacks, Chapters 6 and 7), Jennaway allows the women
to ‘speak’ and express their feelings. This highlights the embodied desire of individual women,
rather than male interests such as status concerns, such that the account nicely subverts domi-
nant anthropological literature with its preoccupation with kin groups and status competition.1
An innovation is the use of fictionalized ethnography, interposed, usually as a page or two in
italics, in often unrelated sections of the book. This device was used primarily in order to better
covey the ‘felt, subjective nature of women’s emotional and erotic experience’ (p.215). I felt
uneasy with these passages, mainly because many were imaginative descriptions of sensual
feelings and I was never sure on what evidence they had been built (e.g. pp.19–20 about Ning’s
excited anticipation that her lover might visit that day). Some, of course, were evocative de-
scriptions of village life that rang true and simply made me homesick for Bali! The ‘sisters’ in
the book title, by the way, refers to three main informants, all sisters, rather than to the social
category, which, rather confusingly, is barely addressed at all.
The book shows the strength of Balinese cultural codes, which stress the desirability of
female modesty and the compulsory nature of marriage, and the contradictory discourses of
maidenly virtue and the need to catch a husband. The sexual double standard, in which cewek
(chicks!) may not indulge their sexual appetites but cowok (guys) may, or perhaps should, is at
play here. As a result, a young woman finds herself caught between two opposed ‘pulls’: on the
one hand, the need to ‘shine’, to attract and keep a young man, which sometimes requires her to
give in to his demands for premarital sex, and on the other, the need to protect her reputation as
a pure and modest, and therefore marriageable, young woman. So strong is the marriage require-
ment that women prefer the ignominy of polygyny to spinsterhood.
The main insight the book offers is its revelations of the ‘transgressive’ practices of love and
desire by which women secure (or lose) their partners. The stories of young women orchestrat-
ing covert and dangerous romantic meetings in order to achieve their heart’s desire and marital
respectability are moving, and the chapter on women’s illnesses (‘hysteria’) as allowable, albeit
temporary, expressions of nonconformity or rebellion interesting. However, questions of soma-
tization as resistance remain outstanding and the term ‘transgressive capital’ is rather mysteri-
ous.
96 ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003
Seniman Tragis dan Karyanya yang Terlupakan
The Gamelan Digul and the Prison Camp Musician
Who Built it:
An Australian Link with the Indonesian Revolution
Penulis: Margaret J. Kartomi
Rochester, NY: University of Rochester Press
2002, xxi + 124 hlm, bibliografi, index, 1 Audio CD (17 track, 30 menit).
Ditinjau oleh: Iwan Dzulvan Amir
(Centre for Strategic and International Studies)
Di tengah memburuknya hubungan diplomatik antara dua negara bertetangga— Indonesia
dan Australia—akibat gejolak politik domestik dan internasional pada era Reformasi, telah
bermunculan berbagai artikel di media dan penerbitan ilmiah yang mengulas berbagai segi
dinamika hubungan ini. Sesuai dengan paradigma différence yang mendominasi era desentralisasi
di Indonesia, tema yang sering dimunculkan sangat terpusat pada perbedaan antara kedua bangsa,
yakni dalam hal pragmatis seperti ekonomi dan politik sampai hal yang sebetulnya sukar
didefinisikan seperti budaya. Dengan kata lain, fokus masih terpusat dalam konteks perbedaan.
Berbagai kalangan yang berusaha mengurangi ketegangan antara kedua negara—terutama dari
kalangan diplomat, akademisi, dan bisnis—menekankan bahwa terdapat banyak persamaan dari
kedua belah pihak yang sesungguhnya sangat kuat dan bisa dijadikan basis mempererat hubungan.
Argumen yang paling sering dilontarkan oleh kalangan ini adalah konflik hanya terjadi pada
tingkat politik, sementara pada tingkat perorangan (person-to-person) hubungan antara kedua
negara malah bertambah baik. Untuk menepis tudingan bahwa Australia menginginkan Indone-
sia yang terpecah dan lemah, kalangan ini juga mengajukan berbagai argumen historis. Salah
satunya, Australia adalah negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda.
Buku The Gamelan Digul and the Prison Camp Musician Who Built it merupakan karya
Prof. Margaret Kartomi, seorang Etnomusikolog dari Monash University ini merupakan tambahan
yang sangat penting dari argumen historis tersebut. Buku ini berwujud setengah biografi dan
setengah kajian budaya seputar perangkat alat musik gamelan langka yang dijuluki gamelan
Digul. Buku ini menambah maraknya penerbitan buku seputar gamelan sepanjang tahun 2002
(buku lainnya seperti Darsono 2002; Soetandyo 2002; dan Sumarsam 2002). Tiga bab pertama
merupakan biografi dari pencipta gamelan Digul, Pontjopangrawit, dan tiga bab terakhir adalah
pengulasan nilai dan peran gamelan Digul dalam peta sejarah hubungan Indonesia-Australia.
Buku ini juga dilengkapi satu CD berisi 17 track lagu dimainkan dengan memakai gamelan
Digul.
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 97
Pontjopangrawit lahir tahun 1893 di Surakarta, Jawa Tengah. Sejak usia 12 tahun beliau
sudah menjadi salah satu musikus Keraton Surakarta Hadiningrat pada masa Sri Sultan Paku
Buwono X (hlm.15). Di sana beliau belajar bermain dan membuat gamelan sehingga menjadi
seorang musikus yang inovatif dan seorang guru yang sangat dicari-cari. Pada masa mudanya,
Pontjopangrawit terlibat aktivitas politik radikal. Perlu diingat bahwa dalam ukuran masanya,
aktivitas politik radikal sangat menjamur di kalangan pemuda Indonesia (termasuk aktivisme
oleh para pendiri bangsa seperti Ir. Sukarno dan Sutan Sjahrir). Karena keterlibatan tersebut,
beliau ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan pada tahun 1926 dijebloskan ke tempat
pembuangan tahanan politik di Boven Digul, Tanah Merah, Irian Barat (hlm.23). Untuk hiburan
selama masa tahanan, Pontjopangrawit bersama rekan-rekan sesama tahanan membuat satu set
gamelan yang dirakit dari bahan-bahan kehidupan sehari-hari seperti sendok dan panci (hlm.31–
32). Gamelan Digul ini telah berjasa menghibur para tahanan selama masa pembuangan.
Pontjopangrawit dilepaskan dari tahanan pada tahun 1932 dan meneruskan profesinya di Keraton
sampai tahun 1948 ketika beliau terpaksa mengundurkan diri karena gaji musikus sudah tidak
mencukupi kebutuhan sehari-hari (hlm.49). Walaupun tidak menjadi staf resmi, beliau masih
sering bermain gamelan pada berbagai acara keraton dan meneruskan mengajar musik tradisional.
Pada awal tahun 1950-an beliau dianugerahi gelar Perintis Kemerdekaan oleh Presiden Sukarno
atas aktivisme politiknya tahun 1920-an, pembuangannya di Boven Digul, dan dukungannya
atas Revolusi Kemerdekaan tahun 1945–1949 (hlm.49). Pontjopangrawit merupakan salah seorang
pendiri Konservatori Karawitan Indonesia yang berdiri pada tanggal 27 Agustus 1950 (hlm.50).
Beliau mengajar di sana sampai pensiun tahun 1963. Sepanjang karirnya di Konservatori,
Pontjopangrawit menghadapi berbagai hujatan ‘komunis eks-Digul’ dari sesama staf dengan
merendah, ‘[Saya] hanya seorang pangrawit (musikus gamelan)’ (hlm.50). Sayang kerendahan
ini tidak bisa melindungi beliau dari ‘pembasmian komunisme’ menyusul Gerakan 30 September
1965. Versi resmi pemerintah (Mensospol bahkan mengeluarkan SK mengenai hal ini) adalah
beliau meninggal 11 Oktober 1971 sementara keluarganya mengatakan bahwa beliau meninggal
dibunuh pada Hari Pahlawan 1965 (hlm.55). Teman dekat Pontjopangrawit mengeluh bahwa
ukiran nisan di makam beliau yang dibuat oleh pemerintah itu keliru tanggal, bulan, dan tahun
kematian bahkan salah mengeja nama beliau (hlm.61). Pontjopangrawit adalah salah satu korban
sejarah dari sebuah bangsa yang sering melupakan sejarah.
Walaupun riwayat hidup Pontjopangrawit berakhir dengan tragis, ciptaannya yaitu gamelan
Digul berhasil terhindar dari nasib yang sama. Gamelan Digul tetap berada di Digul untuk
menghibur para tahanan sampai tahun 1943. Pada saat tentara Jepang menginvasi Irian Barat,
tentara Australia mengevakuasi sekitar 120 orang Indonesia dari Digul ke Australia. Di Austra-
lia, gamelan Digul tetap berfungsi sebagai alat hiburan bagi para tahanan. Pertama-tama para
tahanan ini dianggap sebagai tahanan perang (hlm.64). Melalui berbagai cara para tahanan
berhasil menjelaskan bahwa mereka adalah pejuang kemerdekaan dan bukan pendukung Jepang.
Simpati datang dari berbagai pihak terutama dari kalangan pendukung HAM dan dari partai
Buruh. Mereka akhirnya dibebaskan dari tahanan pada akhir tahun 1943 dan diperkenankan
menetap di Melbourne dari tahun 1944 sampai 1945. Pada masa tersebut gamelan Digul
meneruskan perannya sebagai alat hiburan, kali ini dipakai para bekas tahanan untuk mengenalkan
kebudayaan Indonesia kepada publik Australia (hlm.65–66). Pada masa berlakunya kebijakan
rasis White Australia pertunjukan bekas tahanan tersebut merupakan hal yang luar biasa dan
98 ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003
mampu membuka mata publik Australia akan kompleksitas kebudayaan di Asia, serta memancing
rasa ingin tahu akan pergolakan politik di berbagai negara tetangga. Salah satu hasil nyata dari
hubungan berbasis person-to-person ini adalah boikot buruh perkapalan terhadap kapal-kapal
Belanda sehingga mempersukar kembalinya Belanda di Indonesia pada masa Perang Revolusi
(hlm.70). Ketika para bekas tahanan pulang ke Indonesia pada tahun 1946, gamelan Digul
disumbangkan ke Museum of Victoria. Kini sesudah melalui proses konservasi, gamelan Digul
disimpan di Departemen Musik Universitas Monash.
Ada dua hal yang sangat menyentuh nurani penulis dari membaca buku ini. Pertama, betapa
enggannya bangsa Indonesia menghadapi berbagai hantu dari masa lalu. Tragedi Pontjopangrawit
adalah satu dari banyak tragedi yang telah dilupakan oleh bangsa ini. Walaupun tragedi ini
tergolong relatif baru (hanya tiga dekade yang lampau), tetapi tetap belum ada usaha serius
untuk menggali apa yang sesungguhnya terjadi pada masa kekacauan di pertengahan tahun 1960-
an. Minat akan penggalian sejarah pada era ini masih sangat tergantung dari peneliti asing seperti
Prof. Margaret Kartomi. Karena itu, sangat terbuka kemungkinan adanya salah satu efek
Orientalisme yang ditakutkan Edward Said, yaitu sejarah kebudayaan suatu bangsa menjadi
sangat tergantung akan interpretasi yang dilakukan oleh bangsa lain. Kedua, betapa cepatnya
pemimpin bangsa—baik dari Indonesia maupun Australia—melupakan berbagai ikatan rumit
dalam sejarah hubungan kedua bangsa demi memenuhi kepentingan politik domestik sesaat.
Seandainya para pemimpin tersebut mau belajar dari Pontjopangrawit bahwa kehidupan akan
berjalan terus terlepas dari kepercayaan akan ideologi, dan seandainya mereka juga mau belajar
dari para bekas tahanan Digul bahwa hubungan baik hanya bisa dicapai dengan diplomasi yang
proaktif, berbagai kecurigaan akan menghilang dengan sendirinya. Tentu saja prasyarat utama
dari sikap-sikap ini adalah apresiasi akan sejarah.
Referensi
Darsono
2002 Cokrodihardjo, Sunarto Cipto Suwarno: Pangrawit Unggulan Luar Tembok Keraton.
Surakarta: Yayasan Citra Etnika.
Soetandyo
2002 Kamus Istilah Karawitan. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Sumarsam
2002 Hayatan Gamelan: Kedalaman Lagu, Teori dan Perspektif. Surakarta: STSI Press.
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 99
Melawan Fundamentalisme
The Clash of Fundamentalisms:
Crusades, Jihads and Modernity
Penulis: Tariq Ali
London, NewYork: Verso
2002, x + 342 hlm, appendix, index.
Ditinjau oleh: Iwan Dzulvan Amir
(Centre for Strategic and International Studies)
Dalam pembukaan buku barunya, The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and
Modernity, penulis, aktivis, dan pembuat film, Tariq Ali menulis:
Tragedies are always discussed as if they took place in a void, but actually each tragedy is condi-
tioned by its setting, local and global. The events of 11 September 2001 are no exception ... I want to
write of the setting, of the history that preceded these events, of a world that is treated virtually as a
forbidden subject in an increasingly parochial culture that celebrates the virtues of ignorance, pro-
motes a cult of stupidity and extols the present as a process without an alternative.(hlm.1)
Buku yang mengungkapkan berbagai konfrontasi antara Islam dan dunia Barat ini barangkali
adalah buku perkenalan yang paling baik saat ini mengenai topik tersebut pasca tragedi 11 Sep-
tember 2001. Buku ini merangkum berbagai revolusi sosial di beberapa benua dan meneliti
berbagai aspek agama monolitik dimulai dari abad ke-14 sampai perang Amerika melawan teror.
Ternyata masih banyak warga Amerika yang tidak menyangka bahwa Amerika Serikat itu di
dunia internasional sedemikian tidak disukai secara terbuka. Mereka saat ini sedang sibuk mencari
jawaban dari masalah ini. Ali menanggapi keluguan tersebut sebagai sebuah usaha untuk mencari
penjelasan yang tidak simplistis seperti ‘mereka benci kita karena kita kaya dan merdeka’ (hlm.3).
Tentu saja hal ini tidak sesederhana itu. Ali mengatakan bahwa kita perlu mengerti bukan hanya
keputusasaan, melainkan juga ketakwaan membabi buta yang dapat mendorong seseorang
mengorbankan jiwanya. Jika politisi Barat terus menyepelekan masalah ini, tragedi tersebut
pasti terulang. Memerangi fanatisme sempit dan kejam dengan memakai cara-cara yang sama
sempitnya dan sama kejamnya tidak akan membawa keadilan dan demokrasi (hlm.3). Jadi, kedua
jenis fundamentalisme yang disebut pada judul buku Ali adalah fundamentalisme religius Islam
dan patriotisme ultra-nasionalis Amerika Serikat.
Ali menjelaskan asal-usul dan perkembangan Islam sebagai sebuah proyek spiritual selain
sebuah proses yang didorong tujuan sosio-ekonomi. Deskripsinya tentang Islam awal yang
terbentang dari Eropa ke Asia menunjukkan bahwa Islamisme kontemporer sesungguhnya sangat
terkebelakang dibanding jaman dahulu.
100 ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003
Buku ini melacak secara rinci pasang-surut Islam sepanjang sejarah sambil mengaitkannya
dengan asal-usul berbagai cabang teologis-politis yang diinstitusionalisasikan menjadi berbagai
masyarakat dan gerakan Islam masa kini. Ia menunjukkan bahwa fanatisme dan ketidaktoleriran
bukan hanya monopoli Islam saja. Kritiknya terhadap fundamentalisme Islam didasarkan atas
analisis Marxis terhadap agama yang dilihat sebagai sebuah institusi sosial yang opresif, menjual
delusi, dan memegang kekuasaan untuk mempersekusi.
Deskripsi Ali tentang peranan berbagai organisasi Islamis di berbagai negara yang memerangi
gerakan nasionalis dan komunis, juga kejahatan HAM berbagai kediktatoran pemuka agama
menunjukkan bahwa Islam di abad ke-20 bukanlah sebuah gerakan politik yang progresif. Contoh
terbaru (pada saat ia menulis buku tersebut) yang paling terkenal tentu saja adalah serangan
teroris yang menghancurkan menara kembar World Trade Center.
Kebiadaban 11 September tidak bisa ditolerir, tetapi juga harus dipahami sebagai dampak
dari fundamentalisme neo-liberal. Kemenangan kapitalisme telah menumpuk hampir semua
kekayaan dunia ini di tangan segelintir orang. Bahkan elit di negara berkembang sekalipun hanya
mampu mencoba meniru-niru pola hidup negara kapitalis. Kemarahan, frustrasi, dan keputus-
asaan menumpuk sehingga mendorong segelintir orang untuk hidup di luar hukum.
Ali berpendapat bahwa fundamentalisme Islam kontemporer adalah ‘anak haram’
fundamentalisme imperialis. Dengan mengesampingkan proses demokrasi, imperialisme
menciptakan iklim yang memupuk berbagai jenis ketidakrasionalan. Berbagai gerakan revivalisme
religius adalah akibat langsung ditutupnya berbagai gaya hidup alternatif oleh induk segala
fundamentalisme, yaitu imperialisme Amerika (hlm.281).
Ali memandang teori fatalistik seperti tesis Clash of Civilizations-nya Samuel Huntington
sebagai pandangan reduksionis dan simplistik. Ia menulis bahwa peradaban apa pun tidak ada
yang monolitik. Mereka selalu mengalami kompetisi ideologi politis dan sistem nilai yang
bertentangan.
Over the last hundred years, the world of Islam has felt the heat of wars and revolutions just like every
other society. The seventy-year war between United States imperialism and the Soviet Union affected
every single ‘civilisation’. Communist parties sprouted, grew and gained mass support not only in
Lutheran Germany but in Confucian China and Muslim Indonesia.(hlm.274)
Yang lebih penting lagi menurut Ali, hubungan politik antarkebudayaan pada dasarnya berciri
hubungan keterkaitan, ketergantungan, dan dan saling tumpang tindih, bukan memakai sistem
zero-sum yang melulu berciri konfliktual dan fatalistik.
Sesungguhnya, pesan inti buku Ali ini tidak terlalu berbeda dari karya penulis lainnya seperti
Karen Armstrong (1991 dan 2000), Benjamin Barber (1996), John Esposito (1999 dan 2002),
Chalmers Johnson (2000), dan Edward Said (1979 dan 1981) yang mengungkapkan cara
pemerintah Barat berhubungan dengan dunia Islam. Ali dan para penulis lain tersebut menekankan
pentingnya konteks, yaitu cara fundamentalisme Islam menjelma sebagai reaksi ekstrim terhadap
kebijakan ekonomi dan militer pemerintah Barat. Yang membedakan buku Ali ini dari karya
sebelumnya adalah penekanannya pada elaborasi. Ia menekankan perlunya memerangi berbagai
bentuk jenis penjelasan simplistis yang sangat mudah dimanfaatkan untuk tujuan politik.
Simplisitas inilah yang selalu menjadi senjata andalan berbagai kaum fundamentalis, yakni
fundamentalis Islam, fundamentalis neo-liberal, fundamentalis pasar, dan lain sebagainya.
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 101
Ali juga membuat satu observasi penting yang sesungguhnya merupakan sebuah kebenaran
universal: hamba sahaya tidak selalu mematuhi perintah tuannya. Pergolakan berbasis prinsip
ini telah berkali-kali dialami berbagai pemerintahan yang konon tidak terkalahkan, mulai dari
kekaisaran Romawi sampai hegemoni Amerika Serikat. Sayang, hal ini terlalu sering dilupakan
kalangan politikus.
Buku ini bukanlah kritik Ali yang pertama kali terhadap fundamentalisme agama. Ia sendiri
sudah sering berurusan dengan kalangan fanatik, mulai dari fanatik Islam sampai fanatik ekonomi
pasar. Hal ini tampaknya sudah menjadi risiko yang berani ditanggungnya. Oposisi melawan
segala bentuk fundamentalisme akan selalu mempertentangkan intelektualisme jujur dengan para
aktor agama dan politik yang selalu merangkul ortodoksi masing-masing dogma.
Ali berada dalam posisi unik untuk menulis tentang fundamentalisme Islam. Ia menganggap
dirinya sebagai korban dari fundamentalisme tersebut. Dibesarkan sebagai seorang Muslim di
Pakistan, kini Ali mengakui secara terbuka bahwa dirinya adalah seorang ateis. Di negara yang
memberlakukan hukum Islam, ateisme (apalagi konversi dari Islam) lebih berdosa daripada
kejahatan lain seperti mencuri atau membunuh, dan penganutnya wajib dibunuh. Secara
intelektual, pemikiran radikal Ali menjadikannya semacam pariah kiri. Penindasan akibat kedua
bentuk diskriminasi ini mendorong Ali untuk tidak sungkan dalam mengritik berbagai basis
ideologis yang mendasari ketidaktoleransian dan kebencian irasional dari fundamentalisme.
Di lingkungan penuh kegamangan ideologis seperti Indonesia, tempat kalangan moderat
selalu memilih diam dalam menghadapi retorika dan agitasi kalangan ekstrim, keberanian Ali
layak untuk direnungkan, dan kalau mungkin dicontoh. Hanya ada satu jalan yang harus ditempuh
dalam memerangi pola pikir sempit yang berbasis kecurigaan dan kebencian, yaitu menantangnya
secara langsung, terbuka, jujur, dan rasional.
Referensi
Armstrong, K.
1991 Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam. London: Victor Gollancz.
2000 The Battle for God. New York: Alfred A. Knopf.
Barber, B.R.
1996 Jihad vs. McWorld. New York: Ballantine Books.
Esposito, J.L.
1999 The Islamic Threat: Myth or Reality?. New York: Oxford University Press.
2002 Unholy War: Terror in the Name of Islam. New York: Oxford University Press.
Johnson, C.A.
2000 Blowback: The Costs and Consequences of American Empire. New York: Metro-
politan Books.
Said, E.
1979 The Palestine Question and the American Context. Beirut: Institute For Palestine
Studies.
1981 Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of
the World. London: Routledge & Kegan Paul.
102 ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003
Arkeologi Budaya Indonesia:
Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-artefak
Kebudayaan Indonesia
Penulis: Jakob Sumardjo
Yogyakarta: CV Qalam
2002, xvii + 365 halaman
Ditinjau oleh: Edi Sedyawati
(Universitas Indonesia)
Buku ini merupakan kumpulan sejumlah karangan yang semula ditulis terpisah, dan kemudian
dihimpun dalam suatu kesatuan pokok permasalahan, yaitu apa yang disebut oleh penulisnya
‘pandangan-pandangan primordial Indonesia’. Pandangan ‘primordial’ itu diungkapkannya
berdasarkan upaya semacam ‘rekonstruksi’, dengan menggunakan metode yang disebutnya
‘hermeneutis-historis’ seperti tertera pada judul buku.
Pokok-pokok ‘kajian’ yang dituangkan dalam masing-masing bagian dan bab adalah:
pendahuluan (ringkasan sejarah kerohanian Indonesia), arkeologi primordial (konsep ruang dan
waktu dalam primbon, tafsir gambar-gambar prasejarah, dan membaca selembar ulos Batak),
arkeologi kuno (elemen primordial cerita Bubukshah-Gagang Aking, pantun sebagai produk
budaya Sunda Lama, tafsir kosmologis Topeng Cirebon, dan gambar-gambar Damarkurung
Masmundari), dan arkeologi madya (dua kajian pantun Melayu dan memahami Serat Gatholoco).
Penulis memang mengakui bahwa ia menuliskan isi buku itu ‘secara amatir saja’ karena
tidak menguasai disiplin ilmu antropologi dan filsafat, dan ia berpijak pada ‘temuan para pakar
di bidangnya masing-masing’ (hlm.xiv). Daftar pustaka memang disertakannya di bagian akhir
setiap artikel/bab, namun pengacuan itu secara umum saja, tidak dengan memberitahukan bagian-
bagian khusus dalam karya-karya ilmiah itu yang dikutip atau dirujuk. Ketika menyebutkan ‘19
wilayah suku besar’ di Indonesia yang disebutnya adalah buku J.W.M. Bakker, Filsafat
Kebudayan (Yogya: BPK Gunung Mulia Kanisius, 1984), dan bukan sumber pertamanya, yaitu
C. van Vollenhoven yang mengemukakan penggolongannya atas ‘19 wilayah hukum adat’ di
Indonesia (tiga jilid bukunya, terbagi dalam 4 bagian, berjudul Het Adatrecht van Nederlandsch-
Indië diterbitkan tahun 1918–1933).
Penulis juga tidak menjelaskan dasar pembagiannya atas ‘arkeologi primordial’, ‘arkeologi
kuno’, dan ‘arkeologi madya’. Kalaulah budaya prasejarah yang dijadikan patokan untuk
menafsirkan yang ‘primordial’, mengapa soal primbon masuk ke bagian ini, sementara kita tahu
bahwa setidaknya terdapat dasar klasifikasi di dalamnya yang berasal dari, atau setidaknya paralel
dengan, sumber-sumber Hindu Sanskerta, seperti misalnya pembagian lima unsur-unsur alam
(juga 5 resi Pasupata Saiwa yang juga banyak disebut dalam prasasti-prasasti Jawa Kuna), pekan
yang tujuh hari, dewata yang 8 (astadikpalaka) atau 9 (Nawasanga, wujud-wujud Siwa). Begitu
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 103
juga masuknya pembahasan mengenai seni menggambar ‘damarkurung’ oleh Ibu Masmundari
yang hidup di masa kini ke dalam bagian ‘arkeologi kuno’ tidak jelas alsannya. Mungkin
penggolongan itu disebabkan karena artikel tentang seni gambar Masmundari itu menunjukkan
betapa idiom tata ruangnya yang sama dengan yang ditemukan pada relief candi dan wayang
beber itu adalah berdasarkan ‘pandangan hidup nenek moyang orang Indonesia’, tempat ‘ruang
dan waktu pada dasarnya tunggal; yang tunggal itu plural ekspresinya dan yang plural itu tunggal
esensinya’ (hlm.275).
Tak dapat disangkal, pengetahuan Jakob Sumardjo memang luas. Tetapi, harus dikatakan
juga bahwa analisis dan interpretasinya tidak dilandasi disiplin yang ditegaskan dengan jelas.
Penalaran hermeneutik pun seharusnya memerlukan kejelasan mengenai pokok amatan dan
berbagai konteksnya yang spesifik. Asumsi bahwa ada satu saja pandangan dunia yang ‘primor-
dial’ di Indonesia, seperti yang membayangi seluruh tulisan yang terhimpun dalam buku ini,
kiranya masih harus dipertanyakan dengan keras. Bukankah dalam urusan hukum adat saja konon
ada 19 ragam yang dapat saling dibedakan? Demikian pula dalam konsepsi mengenai kosmos,
mestinya tidak begitu saja dianggap bahwa pandangan dasar di seluruh Indonesia itu sama belaka.
Melihat pokok bahasan serta bibliografi yang disertakan tampak bahwa bagian terbesar sumber
yang digunakan adalah mengenai kebudayaan Jawa, disertai sumber yang amat terbatas mengenai
suku-suku bangsa lain, yang hanya meliputi Sunda, Melayu, Cirebon, Batak, Sawu, Irian, Tolaki,
dan Kaili.
Penulis memang mengatakan bahwa apa yang telah ditulisnya itu barulah ‘... secara sepintas,
dalam pandangan yang digeneralisasi, pada tingkat hipotetik. Dan karenanya masih diperlukan
pembuktian empirik yang lebih cermat’ (hlm.73). Pembuktian ataupun penyanggahan itulah yang
perlu diberikan oleh para peneliti untuk menyambut buku ini. Mudah-mudahan buku ini tidak
terlalu diterima sebagai ‘kesimpulan’ final oleh khalayak pembaca. Di samping kelaikannya sebagai
suatu hipotesis, sejumlah keberatan dapat dilontarkan atas apa yang sudah ditulis dalam buku
tersebut.
Ada beberapa acuan dalam upaya generalisasinya yang perlu dipertanyakan. Salah satunya
adalah pernyataan tafsirnya bahwa agama Buddha Mahayana aliran Wajrayana merupakan pilihan
orang Melayu, yang dibedakannya dengan pilihan orang Jawa yang Hindu. Sudah tentu keterangan
seperti itu tak sesuai dengan fakta ditemukannya berbagai tinggalan bangunan maupun artefak
di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merujuk kepada agama Buddha Mahayana Tantra atau
Wajrayana juga. Demikian pula kurang tepat apabila dikatakan bahwa ‘paham Dewaraja’ itu
berarti ‘raja dianggap dewa itu sendiri’. Memang esensi kedewataan itu (sebagian) dapat diserap
oleh raja, dan itu merupakan prerogatifnya, tetapi raja tidak identik dengan dewa. Demikian
juga tidak tepat kalau dikatakan bahwa ‘selama ini kita melihat ada satu India dan satu Indone-
sia’. Dalam kenyataan wacana ilmiah yang membahas hubungan saling pengaruh antara India
dan Indonesia sejak lama sudah sering dipersoalkan tentang ‘bagian India yang mana’ atau
‘bagian Indonesia yang mana’, dan pada zaman-zaman apa yang terkait dengan pokok-pokok
yang dibahas, apakah itu tentang aliran keagamaan ataukah tentang gaya seni, dll.
Penjelasannya tentang sakala, sakala-niskala, dan niskala sebagai pembagian waktu juga
kurang tepat, karena ketiganya adalah perbedaan taraf dzat. Niskala adalah yang tertinggi dan
terabstrak, yang dapat beremanasi ke dua tataran di bawahnya, berturut-turut. Demikian
selanjutnya penjelasan tentang ‘Lokeswara terbagi dua menjadi Aksobhya dan Ratnasambhawa’
104 ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003
dst. (hlm.40) sungguh membingungkan, karena tataran Lokeswara sebagai dhyani-bodhisattwa
tentunya harus difahami bahwa secara kategoris berada di bawah Aksobhya dan Ratnasambhawa
yang tathagata. Transposisi memang dapat terjadi, tetapi itu hanya dalam konteks mandala, dan
hanya berkenaan dengan pemadanan ‘Kebenaran Tertinggi’ dengan salah satu dewata pilihan
yang ‘diangkat ke atas’.
Walaupun di suatu bagian (hlm.71) penulis mentah-mentah menelan klasifikasi Geertz mengenai
masyarakat Jawa, dan ia mengatakan (lebih tepat: menafsirkan) ‘dalam Islam di Jawa terjadi tiga
varian, yakni Islam abangan, Islam priyayi dan Islam santri’, namun di tempat lain (hlm.66) suatu
penyimpulan yang jitu diungkapkannya, yaitu: ‘Zaman transformasi-transformasi agama dan
budaya di Indonesia, ternyata tidak terjadi secara bersamaan dan menyeluruh’. Tetapi ia pun
dapat tergelincir ke dalam generalisasi yang tidak jelas landasannya, seperti ketika membahas
minat yang meluas tentang tasawuf, saat ia mengidentifikasi penyebabnya, yaitu: ‘Minat religi
bangsa Indonesia sejak zaman prasejarahnya memang pragmatisme ini, dengan pendekatan
holistik-spiritual’ (hlm.62). Sudah tentu kita semua maklum bahwa pemikiran dan cara hidup
orang prasejarah hanya dapat didekati dengan dugaan atau analogi etnografi, sehingga tidak
akan pernah kita dapat mengatakan ‘orang prasejarah memang begini atau begitu’.
Dalam uraian-uraian penafsiran atas berbagai ekspresi budaya, baik dari masa lalu maupun
dari berbagai masyarakat tradisi yang dikenal dewasa ini, ataupun yang menggabung-rentang
semuanya, penulis sering menyajikan suatu othak-athik , yaitu mencocok-cocokkan, meskipun
tanpa landasan keberlanjutan tradisi ataupun keterkaitan kesejarahan. Juga seringkali tidak jelas
apakah informasi tertentu yang sedang disajikannya itu didapat dari pemilik kebudayaan yang
bersangkutan ataukah hasil tafsiran penulis. Penjelasan tentang kata ahung dalam mantra pantun
Sunda sebagai berasal dari mantra Buddha Wajrayana ‘om mani padme hum’ (bukan ‘om nani
padme hum’ seperti dua kali dikutip penulis) pun masih perlu dikaji ulang. Banyak interpretasi
Jakob Sumardjo memang merangsang semangat untuk mempertanyakan kembali. Satu telaah
yang amat baik dilakukannya adalah ketika ia mengamati dan mendeskripsikan proses dan metode
mengggambar yang dilakukan oleh mBah Masmundari (95 tahun, dari Gresik) dalam membuat
damarkurung (lampion), yang selalu dimulainya dengan menggambar di tengah-tengah kertas,
kemudian ke kanan dan selanjutnya hingga kertas itu penuh. Cara ini, menurut penulis, terdapat
‘sejak zaman Borobudur sampai wayang beber dan lukisan kaca...yang berprinsip, bahwa
keberadaan itu, baik yang mikrokosmos, makrokosmos maupun metakosmos, adalah satu
kesatuan, keutuhan, menembus ruang dan waktu’. Demikianlah, banyak detail yang menarik
untuk disimak lebih jauh dari buku ini.
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 105
Pembangunan dan Paradigma Modernisasi:
Di mana kita berada saat ini?
Perubahan Sosial:
Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia
Penulis: Agus Salim,
Yogyakarta: Tiara Wacana
2002, 318 halaman, bibliografi, index.
Ditinjau oleh: Hanneman Samuel
(Universitas Indonesia)
Buku ini terdiri atas beberapa bab yang diawali dengan bab pendahuluan yang berisi uraian
konsep-konsep kunci perubahan sosial dan peta dasar analisis tentang perubahan sosial. Termasuk
dalam bagian ini, uraian tentang pemikiran tokoh-tokoh klasik ilmu sosial tentang perubahan
sosial. Kerangka dasar teori modernisasi dan teori ketergantungan dan imperialisme
dibandingkannya satu sama lain.
Bab III berisi uraian tentang lima pendorong utama pembangunan, yakni: media massa,
birokrasi, modal, teknologi, dan ideologi. Secara khusus, pembahasan tentang ideologi
dikaitkannya dengan Pancasila dan agama. Uraian ini diteruskan dengan membedah teori
perubahan sosial di Asia (bab IV). Perhatian secara khusus difokuskan pada dua hal. Pertama,
pdanangan Hans Dieter-Evers, seorang pakar Asia Tenggara yang produktif yang berbasis di
Jerman. Kedua, mengenai sejarah perubahan sosial di Nusantara.
Pada bab V penulis memaparkan beberapa pendekatan utama dalam penelitian tentang
perubahan sosial. Perhatiannya tampak diarahkan pada pendekatan mikro. Namun hal ini
dilakukan tanpa mengabaikan arti penting pendekatan makro, suatu pendekatan yang seringkali
dianggap berada pada kubu yang bertolak belakang dengan pendekatan mikro.
Setelah melakukan pemaparan tentang berbagai segi teoretis tentang perubahan sosial dan
pembangunan, buku ini ditutup dengan gagasan penulis tentang pembangunan. Ia
mempermasalahkan pembangunan, dan menawarkan gagasan dasar untuk meluruskan
pembangunan kembali ke relnya. Pada bab VI ini, secara tegas penulis mengaitkan
multikulturalisme dengan pembangunan, yang ditempatkannya secara berhadap-hadapan dengan
ethno-development.
Buku ini juga dilengkapi dengan indeks kata-kata penting, sedangkan sumber bacaan yang
digunakan penulis cukup beraneka ragam. Berbagai tulisan pemikir modernitas yang relevan
digunakannya, termasuk karya pemikir Indonesia. Apa yang dapat dikomentari tentang isi buku
Perubahan Sosial ini?
106 ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003
Seperti yang diakui oleh Salim, perubahan sosial merupakan satu hal yang mungkin tidak
akan pernah habis dibahas. Persoalan ini sangat kompleks sehingga setiap penulis harus
menentukan pilihan: membahas perubahan sosial secara sempit-mendalam atau melakukan
pemetaan. Penulis memilih pilihan kedua dengan menyusun kembali diktat berbagai kuliah
yang diikutinya menjadi satu sebagai—ia menyebutnya—peta kasar pandangan tentang perubahan
sosial dan pembangunan. Mungkin hal inilah yang mendorongnya memilih kata sketsa sebagai
anak judul bukunya. Dalam pemetaan tersebut, pengalaman scholarly-nya digunakan sebagai
penapis. Salim telah berbagi ilmu yang diperolehnya di kelas dengan kalangan audience yang
lebih luas. Ini merupakan satu catatan penting saya tentang buku ini .
Ada suatu konsensus di kalangan para pakar yang menekuni perubahan sosial bahwa perubahan
sosial—termasuk di dalamnya, pembangunan—memiliki masa silam, masa kini, dan masa depan.
Salim lebih tertarik pada kekinian, yakni, paradigma modernisasi seperti yang dipraktikkan di
Indonesia. Pemaparan singkatnya tentang varian teori-teori klasik diletakkannya dalam perspektif
tersebut. Di sinilah letak nilai lain dari tulisan ini. Tulisan ini memperkuat keyakinan saya bahwa
sudah saatnya kita melakukan penilaian atas berbagai teori perubahan sosial dan pembangunan
utama (mainstream social change and development theories). Teori-teori tersebut lahir dan
dibesarkan dalam suasana Enlightenment dan modernitas di Eropa Barat dan Amerika Utara,
yang kemudian disebarkan ke berbagai belahan bumi, termasuk ke Indonesia sebagai post-colo-
nial reality.
Perjalanan konsep-konsep perubahan sosial dan pembangunan dalam paradigma modernisasi
merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Konsep-konsep tersebut dan penerapannya tidak
lepas dari paradigma modernisasi. Apa yang membedakan teori modernisasi dari teori
ketergantungan dan imperialisme terletak pada dimaknainya makna positif yang diberikan oleh
pengikut modernisasi secara negatif oleh pengikut ketergantungan. Misalnya transfer of tech-
nology dalam pandangan modernisasi diperlukan dalam pembangunan. Tetapi, hal tersebut
dipandang sebagai upaya melestarikan ketergantungan terhadap negara-negara maju.
Dalam perjalanan panjang tersebut, berbagai pihak telah ikut terlibat mengembangkan
paradigma modernisasi secara saling melengkapi. Hasilnya, pemisahan antara kerja ‘arm chair’,
ideolog, dan kerja perekayasa sosial lebih merupakan slogan (atau mungkin juga, harapan)
daripada kenyataan. Netralitas ilmu sosial terhadap kepentingan politik ekonomi pun sering
menjadi perdebatan berkepanjangan. Apalagi bila pembahasan tentang perubahan sosial
dipusatkan pada persoalan-persoalan pembangunan. Sejarah kaya dengan data mengenai cara
kajian deskriptif-analitis tentang perubahan sosial pada masyarakat maju diimpor ke Asia, Afrika,
dan Amerika Latin. Di sebagian masyarakat, kajian tersebut dianggap sebagai ‘barang’ siap
pakai. Di masyarakat lain, termasuk Indonesia, kajian tersebut dianggap sebagai bahan tiga per-
empat jadi, yang mengalami proses kontekstualisasi. Kesamaannya, di dalam proses ini kajian-
kajian deskriptif-analitis berubah menjadi rumusan preskriptif (Hoogvelt 1981; Suwarsono dan
So 1991; Samuel 2003). Temuan ilmiah di Barat dianggap sebagai kepastian dan cita-cita yang
layak dicapai.
Hal inilah yang mungkin mendorong penulis untuk membuat uraian khusus tentang indigenisasi
ilmu sosial (bab 6). Data yang disajikannya akan lebih menarik sekiranya penulis membandingkan
‘indigenisasi’ dengan ‘nativisasi’, sebuah konsep—menurut Farid Alatas (1993)—menunjuk
pada anti tesis dari proses hegemoni Barat.
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 107
Tentang hal ini, seperti halnya Gardono (1998) dan Kleden (1987), penulis menekankan tentang
perlunya indigenisasi ilmu sosial di Indonesia, bukan indigenisasi macam apa yang diperlukan.
Padahal ‘indigenisasi ilmu sosial’ itu bak karet gelang. Semakin ditarik, semakin memanjang.
Alatas (1993) menawarkan ilmu sosial Islam untuk indigenisasi ilmu sosial di Dunia Ketiga. Said
(1978) mengajukan tawaran yang berbeda. Indigenisasi ilmu sosial dipandangnya sebagai
pengembangan ilmu sosial minus colonial scholarship dan orientalist discourse. Gardono (1998)
menawarkan gagasan indigenisasi sebagai informasi ilmiah—informasi yang dilandaskan pada
kenyataan sosial dan diperoleh melalui metodologi ilmiah. Tawaran ini sedikit banyak lebih maju
daripada usulan Association of Asian Social Science Research Council (1983). Kleden berangkat
dari titik yang berbeda. Seandainya garis merah bisa ditarik di antara tulisannya (1987) dengan
tulisan lainnya [Nordholt dan Visser (peny) 1995], mungkin yang dimaksudnya dengan
‘indigenisasi’ adalah pengembangan ilmu sosial sebagai ilmu tentang masyarakat daripada ilmu
untuk kepentingan negara. Samuel (2000) memandang indigenisasi ilmu sosial sebagai ilmu dan
institusi keilmuwan yang semi autonomous.
Secara umum, buku Perubahan Sosial ini merupakan materi yang cukup menarik untuk
bercermin. Bercermin untuk merenungkan kembali makna dan praktik pembangunan di Indone-
sia. Buku ini mengingatkan kita bahwa perenungan apa pun tentang pembangunan dan perubahan
sosial selayaknya dilakukan dalam dialog dengan kenyataan hidup, perenungan yang didasarkan
pada kenyataan hidup, dan perenungan yang dibentuk dalam konteks aplikasi (praxis).
Pembangunan memang lebih dari sekedar permainan kata-kata indah. Ia merupakan, seperti
yang dianut oleh PBB, hak yang dimiliki setiap manusia, baik dalam bidang ekonomi, politik,
maupun kultural.
Salim telah membuka kembali lahan untuk memikirkan secara sungguh-sungguh right to
development, demi kehidupan umat manusia yang lebih bermutu. Hal ini sejalan dengan, misalnya,
gagasan yang dikemukakan oleh Sen (1999). Ukuran-ukuran mutu kehidupan itu sendiri senantiasa
diperbaiki. Penulis tampaknya menyadari hal ini. Ia mencantumkan secara khusus pembahasan
tentang multikulturalisme, sedangkan pluralisme mulai ditanggalkannya. Sayang penulis kurang
mengelaborasi pemahamannya tersebut.
Dia mengatakan bahwa negara merupakan aktor penting dalam pembangunan di Indonesia.
Hal ini bukan tipikal. Di berbagai konteks Asia, Afrika, dan Amerika Latin, negara merupakan
aktor penting dalam proyek modernitas pasca Perang Dunia II. Yang berbeda, hanya reaksi
lokalnya. Reaksi orang Indonesia, berbeda (atau, mungkin lebih tepat, dibuat berbeda) dengan
reaksi orang Filipina. Berbeda juga dengan reaksi orang Singapura.
Sesungguhnya, bukan hanya negara yang penting dalam pembangunan. Universitas merupakan
institusi lain yang memegang peranan penting. Ia merupakan wadah utama kultivasi pembangunan
dan modernitas dalam garis besarnya, yang sama tuanya dengan Enlightenment (Gibbons 1994;
Seidman 1994). Di sini, reorientasi tentang pembangunan yang diusulkan oleh penulis ikut
memperhitungkan hal ini. Ia sudah membuka satu ‘pintu’ lagi untuk pembaca, khususnya yang
tertarik untuk melakukan uraian khusus tentang hal ini secara komprehensif.
Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah sumbangan civil society actors dalam pembangunan.
Terdapat anggapan yang masih cukup kuat bahwa mereka merupakan ancaman terhadap
pembangunan di Indonesia. Tentunya hal ini akan berbeda bila kita beranjak dari titik
keberangkatan yang mengakui bahwa tidak ada satu pihak pun yang mampu mewujudkan
108 ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003
pembangunan single-handedly. Pembangunan yang berkesinambungan menuntut kebersamaan.
Dalam kebersamaan, masing-masing pihak mengakui keterbatasan sendiri dan mengakui
keunggulan pihak lain. Dengan kata lain, pihak yang berbeda dipdanang sebagai mitra yang
sama-sama punya martabat dan harga diri. Bukan sebagai musuh bebuyutan.
Ada satu hal yang, bagi saya, agak mengganggu yaitu diskusi Salim tentang pembangunan
pendidikan. Hal ini dilakukannya pada dua bagian, sementara buku ini secara keseluruhan lebih
melihat pembangunan dalam artian umum. Mungkin akan lebih baik bila diskusi tentang
pembangunan pendidikan diletakkannya sebagai suatu tulisan tersendiri yang sesungguhnya
mampu dilakukannya. Hal ini telah ditekuninya dengan setia selama puluhan tahun.
Sekali lagi, penulis, secara cukup menarik, telah menyajikan bahan baku bagi kita untuk
merenungkan kembali konsep perubahan sosial dan praktik pembangunan. Tulisan ini menambah
perbendaharaan kita, khususnya perbendaharaan tulisan dalam bahasa Indonesia. Langkah
selanjutnya tentu terserah kepada kita. Salah satunya, refashioning ilmu-ilmu sosial sendiri,
tempat martabat manusia merupakan inspirasi utama di era globalisasi pasca Perang Dingin.
Perubahan sosial, pembangunan, dan ilmu sosial sendiri memang sudah sepatutnya bermoral,
seperti yang telah diajarkan oleh para pemikir ilmu sosial klasik.
Referensi
Sen, A.
1999 Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf.
Alatas, S.F.
1993 ‘On the Indigenisation of Academic Discourse’, Alternatives 12(1):37–58.
Association of Asian Social Science Research Council
1983 Social Sciences in Asia in the 1980s: Tasks and Challenges. Selected Papers from the
4th AASSREC Conference. New Delhi: AASSREC.
Gardono, I.
1998 ‘Indigenisasi Sosiologi di Indonesia’, Masyarakat Indonesia 20(2):25–44.
Michael G., C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, dan M. Trow.
1994 The New Production of Knowledge: the Dynamics of Science and Research in Con-
temporary Societies. London: Sage Publications.
Hoogvelt, A.M.M.
1981 The Sociology of Developing Societies. London: MacMillan.
Kleden, I.
1987 Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES.
Nordholt, N.S. dan L. Visser (peny.)
1995 Social Science in Southeast Asia: From Particularism to Universalism. Amsterdam:
VU University Press.
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 109
Samuel, H.
2000 The Development of Sociology in Indonesia: The Production of Knowledge, State
Formation and Economic Change. Tesis Ph.D. tidak diterbitkan. Swinburne: Swinburne
University of Technology.
2003 ‘Indonesian Social Sciences: Looking Back, Creating the Future’. A paper presented
at the ‘Regional Cooperation and Identity Building in East Asia in the Age of Post
Cold War Globalisation: A Search for Institutional Frameworks in Political, Eco-
nomic, Social, and Cultural Fields’, organised by Korean Association for South East
Asian Studies dan ASEAN University Network, the Philippines, 19–22 Feburari.
Said, E.W.
1978 Orientalism: Western Conceptions of the Orient. London: Penguin Books.
1994 Culture and Imperialism. London: Vintage.
Seidman, S.
1994 Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era. Oxford: Blackwell.
Suwarsono dan A.Y. So.
1991 Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
110 ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003
Aneka Pendekatan Studi Agama
Penyunting: Peter Connolly, Pengantar: Ninian Smart
Penerjemah: Imam Khoiri, Nurul Huda S.A.
Yogyakarta: LKiS
2002, xvi + 384 halaman
Ditinjau oleh: Cecep Rukendi
(Universitas Indonesia)
Kajian mengenai agama sebenarnya sudah sangat tua dan telah ada sejak zaman filosof Yunani
dan Romawi. Namun, kajian mengenai agama terlalu didominasi oleh teologi dan humanitas
yang berperspektif agama Kristen sehingga Aquinas mengemukakan bahwa teologi adalah queen
of sciences (Boume 1965). Secara historis, munculnya studi agama bermula dari ekspedisi Barat
(Ilmuwan Eropa dan Amerika) terhadap dunia lain. Mereka mendapatkan bahwa masyarakat
dunia lain ternyata memiliki budaya dan agama yang berbeda yang menjelaskan hal yang sama
tentang yang profan dan yang sakral. Hal ini pada akhirnya memunculkan suatu minat untuk
membandingkan antara kebudayaan dan agama yang satu dengan kebudayaan dan agama lainnya
menurut kacamata Barat. Hal ini ditandai dengan munculnya disiplin comparative religion yang
kemudian berubah menjadi historical religion dengan dipelopori Max Muller. Istilah tersebut
yaitu comparative religion dan historical religion terasa berbau etnosentris Barat dalam mengkaji
budaya dan agama lain terutama timur. Swidler dan Mojzes (2000:57–58) berpendapat agar
disiplin baru ini terlihat inklusif dan luas, dinamai dengan istilah studi agama (study of religion).
Studi agama tersebut—seperti yang dikemukakan Ninian Smart dalam pengantar buku ini
(hlm.vii)—muncul sejak tahun 1960-an yang merupakan perpaduan antara studi-studi historis,
ilmu perbandingan, dan ilmu sosial yang berpuncak pada filsafat agama. Meskipun terjadi
perdebatan mengenai tempat studi agama: apakah dalam departemen teologi atau ilmu sosial,
mayoritas ilmuwan pada akhirnya menempatkannya dalam departemen cultural studies. Dalam
hal ini, studi agama mencakup berbagai metode dan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu yang
sebagian ditulis dalam buku ini, sehingga ia memiliki pengaruh luas dalam pengembangan ilmu
pengetahuan.
Buku yang berjudul asli ‘Approaches to the Study of Religion’ ini merupakan buku pengantar
atau pengenalan awal bagi para pemula yang tertarik mempelajari studi agama. Buku ini memuat
tujuh artikel berisi tujuh pendekatan dalam studi agama yang sering digunakan, yaitu: pendekatan
antropologis, feminis, fenomenologis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan teologis. Ketujuh
pendekatan studi agama tersebut ditulis oleh tujuh orang yang memiliki otoritas keilmuan di
bidangnya masing-masing.
Seluruh pendekatan yang dideskripsikan dalam buku ini berupaya—dengan caranya sendiri—
untuk memetakan—paling tidak sebagian—wilayah agama (hlm.6). Untuk membantu pembaca
dalam memahami dan mengkaji masing-masing pendekatan, Peter Connolly sebagai penyunting
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 111
memaparkan seperangkat alat untuk membantunya (hlm.10), yaitu:
• menguraikan definisi agama sebagai berbagai keyakinan yang mencakup penerimaan pada
yang suci (sacred), wilayah transempiris, dan berbagai perilaku (spiritualitas) yang
dimaksudkan untuk mempengaruhi relasi seseorang dengan wilayah transempiris itu. Agama
dapat bersifat komunal dan individual seperti yang terkandung dalam semua pendekatan
yang ditulis dalam buku ini;
• tulisan dibagi dalam tiga bagian pokok di bawah judul yang sama, yaitu: perkembangan
historis, karakteristik dasar, persoalan dan perdebatan, kecuali pendekatan teologis yang
ditulis dengan sistematika tersendiri; dan
• digunakannya sistem cross-reference (penunjukan silang) antartulisan dimaksudkan guna
memberikan kesempatan pada pembaca menyelidiki posisi pemikir-pemikir atau ide-ide kunci
dalam berbagai disiplin.
Selain ketiga ciri di atas, buku ini juga penting karena pada bagian akhir masing-masing
tulisan, penulis merekomendasikan beberapa buku bacaan lanjutan, baik yang sudah dikutip
dalam artikel maupun yang belum untuk pemahaman lebih lanjut mengenai masing-masing
pendekatan. Kelebihan lain buku ini yaitu selain diuraikannya sejarah dan karakteristik dasar
masing-masing pendekatan, juga dilengkapi dengan studi kasus dan contoh hasil penelitian para
ahli di zamannya masing-masing, baik yang klasik maupun kontemporer.
Sesuai dengan urutan abjad, artikel pertama yang ditulis oleh David N. Gelner menguraikan
tentang pendekatan antropologis. Dalam pendekatan antropologi ini, agama dilihat sebagai suatu
sistem budaya. Gelner memulai tulisannya dengan memperkenalkan perspektif dan contoh
penelitian yang telah dilakukan oleh aliran evolusionis, seperti Frazer dan Durkheim dalam meneliti
agama pada masyarakat terbelakang pada abad ke-19. Ia melanjutkan uraiannya dengan aliran
partikularisme historis Franz Boas yang menekankan metode penelitian lapangan yang detil;
fungsionalisme dan strukturalisme fungsional Malinowski dan Radcliffe-Brown. Gelner juga
memaparkan perspektif antropologi yang lebih kontemporer yaitu Strukturalisme Levi-Strauss,
interpretivisme Clifford Geertz, hingga antropologi feminis yang diwakili Lynn Bennet. Satu hal
yang baik dalam tulisan Gelner adalah diberikannya contoh kasus studi etnografi dari masing-
masing aliran dalam pendekatan antropologi yang dipaparkan.
Gelner menguraikan karakteristik dasar pendekatan antropologi, di antaranya: holisme, dalam
pengertian bahwa agama tidak bisa dilihat sebagai sistem otonom yang tidak terpengaruh oleh
praktik-praktik sosial lainnya (hlm.34); juga thick description yang diperkenalkan Geertz. Di
akhir tulisan, Gelner menguraikan 6 persoalan yang menjadi perdebatan dalam karya-karya
antropologis (hlm.56–58), yaitu:
• apakah ada suatu wilayah keagamaan yang transkultural atau spiritual yang dipahami oleh
manusia seluruh dunia dengan cara yang berbeda-beda?;
• apakah seluruh agama pada dasarnya harus diinterpretasikan dengan cara yang sama atau
tidak?;
• apakah agama bersifat konservatif atau revolusioner?;
• sejauhmanakah seseorang dapat melihat keyakinan keagamaan orang lain tampak dapat
dipahami dan rasional?;
• apakah agama memberikan jalan keluar yang memperoleh dukungan secara kultural dalam
arti kebudayaan lain menganggapnya sebagai bentuk patologi atau bentuk personalitas yang
112 ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003
anti sosial?; dan
• dalam agama-agama yang memiliki kitab suci, seberapa relevan kitab-kitab itu untuk
memahami keyakinan-keyakinan pengikutnya yang awam?
Artikel pendekatan feminis ditulis oleh Sue Morgan. Menurutnya, pendekatan ini bersifat
multidisipliner baik dari antropologi, teologi, sosiologi, dan filsafat. Tujuan feminis dalam studi
agama adalah mengidentifikasi sejauhmana terdapat persesuaian antara pandangan feminis dan
pandangan keagamaan terhadap kedirian, dan cara menjalin interaksi yang paling menguntungkan
antara yang satu dengan yang lain (hlm.63). Dimensi kritis dari pendekatan feminis ini ialah
menentang pelanggaran historis terhadap ketidakadilan dalam agama, dan praktik-praktik
eksklusioner yang melegitimasi superioritas laki-laki dalam setiap bidang sosial (hlm.64).
Sejarah munculnya feminisme religius Anglo-American yang terorganisir muncul pada abad
19 yang didominasi oleh dua isu utama, yaitu: perdebatan tentang persamaan akses terhadap
jabatan pendeta (ministry) dan kritisisme Injil (hlm.65). Selanjutnya, perspektif feminisme
kontemporer (dimulai tahun 1960–1970-an) tetap mengacu pada pembahasan yang komprehensif
terhadap misoginitas agama Barat sebagaimana pendahulunya (hlm.71). Menurut Morgan
(hlm.77), sejak tahun 1980, pertumbuhan dan diversifikasi pendekatan feminis dicirikan dengan
upaya untuk menciptakan sumber material baru dan digunakannya paradigma kesarjanaan
keagamaan yang baru, memperbaiki model androsentris sebelumnya dengan mengistimewakan
pengalaman perempuan.
Adapun perdebatan utama dalam pendekatan feminis yang diangkat dalam tulisan ini ialah
masalah kebutuhan perspektif feminis untuk mengukuhkan suatu kerangka kerja teoretis yang
solid guna terselenggaranya dialog antariman dan antarbudaya di antara perempuan, dan persoalan
separatisme feminis. Pada akhirnya, Morgan menyimpulkan (hlm.101) bahwa pendekatan feminis
telah dan terus berfungsi sebagai suatu percobaan untuk menguji kemampuan agama
mendefinisikan kebermaknaannya sendiri dalam konteks pluralis kontemporer dan menghadapi
tantangan postmodernitas.
Pendekatan fenomenologis selanjutnya ditulis oleh Clive Erricker yang menyatakan bahwa
pendekatan ini merupakan suatu pendekatan dalam studi agama yang mempertimbangkan
keterlibatan peneliti dalam subjek penelitiannya itu sendiri (hlm.107). Pendekatan ini dipengaruhi
oleh filsafat Hegel—esensi dipahami melalui penyelidikan atas penampakan dan manifestasi—
dan filsafat Edmund Husserl yang menguraikan epoche dan pandangan eidetik .
Fenomenologi sebagai suatu gerakan tidak lain dari penuntut status studi agama ilmiah dan
bahwa keragaman klasifikasi, objek, dan metode kajian menunjukkan pluralisme fenomenologi
di bawah suatu disiplin (hlm.29). Keragaman klasifikasi, objek studi, dan metode kajian ini yang
masih menjadi persoalan dan perdebatan dalam pendekatan fenomenologis hingga saat ini.
Berbeda dengan tulisan sebelumnya, Rob Fisher memberikan uraian panjang lebar dalam
pendahuluan mengenai apa itu filsafat, mitos atau persepsi umum tentang filsafat, dan krisis
dalam pendekatan filsafat. Fisher (hlm.155) menyatakan bahwa pendekatan filosofis terhadap
agama adalah suatu proses rasional. Dalam banyak hal, sejarah pendekatan filosofis dalam studi
agama merupakan sejarah pergulatan hubungan antara filsafat dengan agama. Dalam hal ini,
Fisher (hlm.165) mengidentifikasi lima posisi utama mengenai hubungan antara filsafat dengan
agama yang selama ini muncul dalam seluruh sejarah perdebatan, yaitu: filsafat sebagai agama;
filsafat sebagai pelayan agama; yang membuat ruang bagi keilmuan; filsafat sebagai suatu
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 113
perangkat analisis bagi agama; dan filsafat sebagai studi tentang penalaran yang digunakan
dalam pemikiran keagamaan.
Dalam tulisannya tersebut, Fisher (hlm.175–183) juga menguraikan tiga wilayah yang menarik
minat dan penelitian yang menjadi persolaan dan perdebatan dalam pendekatan filsafat, yaitu
1) studi bahasa keagamaan dan dapat disebut dengan pemahaman agama (kultural linguistik);
2) persoalan kejahatan dan terfokus pada teodici dalam kaitan dengan penderitaan dan
kesengsaraan; dan 3) persoalan perbuatan Tuhan di bumi, suatu cara singkat yang mengacu pada
sejumlah persoalan yang lebih spesifik.
Penyunting buku ini, Peter Connolly, ikut menyumbangkan tulisan mengenai pendekatan
psikologis. Pendekatan psikologis ini mengkaji dan meneliti tentang kehidupan beragama pada
seorang individu dengan mempelajari pengaruh keyakinan agama pada sikap dan perilakunya.
Pendekatan ini melihat bahwa agama merupakan suatu fenomena kejiwaan. Sekilas, pendekatan
ini tampak sangat bergantung pada subjektivitas peneliti. Untuk menghindari klaim subjektivitas
tersebut, Connolly (hlm.191–192) menawarkan cara untuk membedakan antara psikologi agama
(psychology of religion) dan psikologi keagamaan (religious psychology). Menurutnya, psikologi
agama mengacu pada penerapan metode-metode dan data psikologis ke dalam studi tentang
keyakinan, pengalaman, dan sikap keagamaan; sedangkan psikologi keagamaan mengacu pada
penggunaan metode dan data psikologi oleh orang yang agamis dengan tujuan memperkaya dan
atau membela keyakinan-keyakinan, pengalaman, dan perilaku keagamaan.
Terdapat banyak mazhab dalam pendekatan psikologis ini. Namun secara garis besar maszhab
itu dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan metode penelitian yang digunakan, yaitu: psikologi
kuantitatif dan kualitatif. Connolly (hlm.201) menguraikan bahwa psikologi kuantitatif meliputi
psikologi fisiologis, behaviourism, psikologi kognitif, dan psikologi sosial. Sementara psikologi
kualitatif meliputi berbagai mazhab psikodinamik yang terkait dengan teoretisi-teoritisi
berpengaruh seperti Sigmund freud (psikoanalisis), Carl Gustav Jung (psikologi analitik), dan
Melanie Klein (psikologi objek relasi), termasuk psikologi humanistik, eksistensial, dan psikologi
transpersonal. Beberapa mazhab yang sangat berpengaruh diuraikan dalam tulisan Connolly ini.
Selanjutnya, M.S. Northcott yang menulis tentang pendekatan sosiologis menyatakan
(hlm.267) bahwa fokus perhatian pendekatan tersebut pada interaksi antara agama dengan
masyarakat. Praanggapan dasar dari perspektif sosiologis ini adalah concern-nya pada struktur
sosial, konstruksi pengalaman manusia, dan kebudayaan termasuk agama. Para sosiolog
memandang objek-objek, pengetahuan, praktik-praktik, dan institusi-institusi dalam dunia sosial
sebagai produk interaksi manusia dan konstruksi sosial. Dengan demikian, agama dalam perspektif
sosiologis dipandang sebagai suatu bentuk konstruksi sosial.
Sama dengan uraian penulis-penulis sebelumnya, Northcott juga menguraikan perkembangan
historis pendekatan sosiologis terhadap agama semenjak kelahiran dari karya-karya para pendiri
sosiologi seperti Comte, Durkheim, Marx, hingga Weber. Dalam hal ini, pembaca memperoleh
penjelasan tidak hanya apa itu pendekatan sosiologis terhadap agama, tetapi juga mengenai apa
itu sosiologi. Selain itu, Northcott juga menguraikan bahwa pendekatan sosiologis juga concern
mengkaji dan meneliti mengenai karakter komunitas keagamaan yang tertutup atau terbatas seperti
biara, sekte-sekte tertentu, hingga gerakan keagamaan baru (new religious movement).
Persoalan dan perdebatan utama dalam sosiologi agama hingga saat ini (kontemporer) menurut
Northcott (hlm.299), adalah perdebatan antara pembela dan penentang tesis sekularisasi yang
114 ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003
mendominasi teori sosial sejak Comte dan Durkheim. Sekularisasi ini mengacu pada proses
ketika agama kehilangan dominasi atau signifikansi sosial dalam masyarakat.
Artikel terakhir yang ditulis oleh Frank Whaling menjelaskan tentang pendekatan teologis.
Berbeda dengan pendekatan lainnya, fokus kajian dalam pendekatan teologis adalah wilayah
dalam agama. Sesuai dengan namanya yang berasal dari kata Yunani, theos dan logos—studi
atau pengetahuan tentang Tuhan atau tuhan-tuhan—kajian dan penelitian yang dilakukan teologi
adalah dalam rangka meningkatkan keimanan dan mencari penjelasan yang rasional dari ajaran-
ajaran agama yang bersangkutan. Oleh karena itu, muncullah teologi Kristen, teologi Islam,
teologi Hindu, dan sebagainya. Mengingat fokus kajiannya yang berbeda dengan pendekatan
lainnya, Whaling menyusun artikelnya dengan sistematika yang berbeda. Ia menjelaskan
bagaimana hubungan antara teologi dan studi-studi keagamaan yang saling membutuhkan, tetapi
masih debatable di kalangan para peminatnya. Selanjutnya, selain menjelaskan teologi agama-
agama, teologi-teologi agama perbandingan, dan teologi agama, Whaling juga menguraikan
sekilas tentang teologi agama-agama global ke arah etika global.
Buku ini dapat menumbuhkan rasa ‘bosan’ bagi para pembaca yang sudah advanced dalam
studi agama. Hal ini disebabkan masing-masing artikel tidak langsung (to the point) menjelaskan
masing-masing pendekatan, tetapi memulainya dari akar sejarah dan permasalahan masing-
masing disiplin ilmu. Oleh karenanya buku ini cocok sebagai acuan bagi para pemula atau
mahasiswa yang hendak memilih pendekatan mana dalam studi agama yang sesuai dengan
minatnya.
Referensi
Swidler, L. dan P. Mojzes.
2000 The Study of Religion in an Age of Global Dialogue. Philadelphia: Temple Univer-
sity Press.
Boume, V.J.
1965 Aquinas’ Search for Wisdom. Milwaukee: Bruce.
ANTROPOLOGI INDONESIA 70, 2003 115
S-ar putea să vă placă și
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryDe la EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryEvaluare: 3.5 din 5 stele3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)De la EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Evaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (121)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceDe la EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (588)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaDe la EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (266)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingDe la EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingEvaluare: 3.5 din 5 stele3.5/5 (400)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe la EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (838)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeDe la EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (537)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerDe la EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (271)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe la EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (5794)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyDe la EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyEvaluare: 3.5 din 5 stele3.5/5 (2259)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersDe la EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (344)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnDe la EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (234)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreDe la EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (1090)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceDe la EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (895)
- Her Body and Other Parties: StoriesDe la EverandHer Body and Other Parties: StoriesEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (821)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureDe la EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureEvaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaDe la EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (45)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)De la EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Evaluare: 4 din 5 stele4/5 (98)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealDe la EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealEvaluare: 4 din 5 stele4/5 (74)
- Epicure - September 2015Document140 paginiEpicure - September 2015mariusÎncă nu există evaluări
- The Bali-Dutch Wars, 1846-1849 Dirk Teeuwen MSC, Holland: ContentsDocument26 paginiThe Bali-Dutch Wars, 1846-1849 Dirk Teeuwen MSC, Holland: ContentsEugene Gorb100% (1)
- Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Sebagai Landasan Pendidikan Dalam Konteks Pendidikan Nasional PDFDocument333 paginiFilsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Sebagai Landasan Pendidikan Dalam Konteks Pendidikan Nasional PDFIndriyani Agustina100% (3)
- (Surya P. Subedi) International Investment Law Re (BookFi) PDFDocument253 pagini(Surya P. Subedi) International Investment Law Re (BookFi) PDFAhmed RyuzakarÎncă nu există evaluări
- Riyanta Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif) PDFDocument24 paginiRiyanta Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif) PDFadang hermeneutikaÎncă nu există evaluări
- Administrative LawDocument120 paginiAdministrative Lawadang hermeneutikaÎncă nu există evaluări
- 98general InformationDocument5 pagini98general Informationadang hermeneutikaÎncă nu există evaluări
- Lampiran Hasil Perhitungan Validitas Dan ReliabilitasDocument3 paginiLampiran Hasil Perhitungan Validitas Dan Reliabilitasadang hermeneutikaÎncă nu există evaluări
- Perhitungan Regres Dengan SpssDocument1 paginăPerhitungan Regres Dengan Spssadang hermeneutikaÎncă nu există evaluări
- Penolakan Grasi Pidana Mati PDFDocument12 paginiPenolakan Grasi Pidana Mati PDFadang hermeneutikaÎncă nu există evaluări
- Fae 18 1 2000 1 PDFDocument8 paginiFae 18 1 2000 1 PDFadang hermeneutikaÎncă nu există evaluări
- Review of Odishan Cultural Interaction With BaliDocument5 paginiReview of Odishan Cultural Interaction With BaliPranab PattanaikÎncă nu există evaluări
- Malioboro ArchitectureDocument51 paginiMalioboro ArchitectureAngga SetyawanÎncă nu există evaluări
- PTS RecountDocument20 paginiPTS RecountRidwan RidwanÎncă nu există evaluări
- ULANGAN HARIAN Mapel Bahasa InggrisDocument14 paginiULANGAN HARIAN Mapel Bahasa Inggrisfatima zahraÎncă nu există evaluări
- Claudia Jane - Esai Ritz CarltonDocument5 paginiClaudia Jane - Esai Ritz CarltonMeerkat BeagleÎncă nu există evaluări
- What Is Introduction ?Document26 paginiWhat Is Introduction ?Reky Wardana100% (1)
- Read The Following Texts and Answer Questions Following. Text 1 Is For Questions No 1 - 4Document9 paginiRead The Following Texts and Answer Questions Following. Text 1 Is For Questions No 1 - 4SadirinIrinÎncă nu există evaluări
- Ookla Rev2Document406 paginiOokla Rev2AdheÎncă nu există evaluări
- Soal Pas Bahasa Inggris Kelas 10Document8 paginiSoal Pas Bahasa Inggris Kelas 10justinÎncă nu există evaluări
- Kuta Weekly-Edition 325 "Bali"s Premier Weekly Newspaper"Document20 paginiKuta Weekly-Edition 325 "Bali"s Premier Weekly Newspaper"kutaweeklyÎncă nu există evaluări
- Bahasa Inggris - 20 SoalDocument9 paginiBahasa Inggris - 20 SoalAnnisa PutriÎncă nu există evaluări
- Kembali20 Partnership Proposal Price Upon Req Rev 21augDocument12 paginiKembali20 Partnership Proposal Price Upon Req Rev 21augMuhammad IlhamÎncă nu există evaluări
- Beige and Orange Minimalist Travel To Bali PresentationDocument10 paginiBeige and Orange Minimalist Travel To Bali Presentationdoden2607Încă nu există evaluări
- Upacara Ngusaba Bukakak: Kontestasi Masyarakat Dan Daya Tarik WisataDocument6 paginiUpacara Ngusaba Bukakak: Kontestasi Masyarakat Dan Daya Tarik WisataSartikaÎncă nu există evaluări
- Brosur TransaksipulsakuDocument256 paginiBrosur TransaksipulsakuALL ABOUT USÎncă nu există evaluări
- Pengayaan PM (Soal)Document8 paginiPengayaan PM (Soal)RifqiDwichandra Crossbonez-paramore AlfajriÎncă nu există evaluări
- Latihan SoalDocument17 paginiLatihan Soal19 Meida Nur HanifaÎncă nu există evaluări
- BQDocument85 paginiBQirfanÎncă nu există evaluări
- I Nerary Day 1: 732 Trips - 218 ReviewsDocument5 paginiI Nerary Day 1: 732 Trips - 218 ReviewsBalasai SabarinathÎncă nu există evaluări
- Rekomendasi InstagramDocument19 paginiRekomendasi Instagramstar cemerlang saranaÎncă nu există evaluări
- CambaMELC910 2nd QuarterDocument16 paginiCambaMELC910 2nd QuarterSarena BitasÎncă nu există evaluări
- C. I'm Fine, TooDocument27 paginiC. I'm Fine, TooDhea Amanda RambeÎncă nu există evaluări
- Soal SMTR Eng Tour XIDocument9 paginiSoal SMTR Eng Tour XIAja KusumaÎncă nu există evaluări
- Bali Options: Bali Hospitality Group Mobile: Phone: Fax: Email: WebsiteDocument5 paginiBali Options: Bali Hospitality Group Mobile: Phone: Fax: Email: WebsiteRama DanuarthaÎncă nu există evaluări
- Bali Major 2023 - Media Handbook 1Document25 paginiBali Major 2023 - Media Handbook 1mikeionaÎncă nu există evaluări
- Javanese Understanding Indic CalendarDocument48 paginiJavanese Understanding Indic Calendarrakawi padeleganÎncă nu există evaluări
- Kŭă ĂƌăɛǁĂƚŝ Tŝěljăwăƌăŵăěśljăŭɛă /E LJăŵɛƶů W Dƶěƌă / Zƶěădăŷŝŭ /T ǁăŷğŷěƌŝ Ed ZƶŵăǁĂŷ Ăůăŝŷ /W Ƶğđă Ew Ƶăƌƚŝŭă 'D Ƶɛăŷƚă /E Ƶƌljăěă /' Tŝěũă /D ĂɛƚăǁĂŷ /T Ƶƌljăěă /' Ăƌğů DƶŭƚŝǁŜďžǁŽDocument14 paginiKŭă ĂƌăɛǁĂƚŝ Tŝěljăwăƌăŵăěśljăŭɛă /E LJăŵɛƶů W Dƶěƌă / Zƶěădăŷŝŭ /T ǁăŷğŷěƌŝ Ed ZƶŵăǁĂŷ Ăůăŝŷ /W Ƶğđă Ew Ƶăƌƚŝŭă 'D Ƶɛăŷƚă /E Ƶƌljăěă /' Tŝěũă /D ĂɛƚăǁĂŷ /T Ƶƌljăěă /' Ăƌğů DƶŭƚŝǁŜďžǁŽHilal ToÎncă nu există evaluări
- Soal Paket 1Document12 paginiSoal Paket 1maselÎncă nu există evaluări